Judul : Get Lost
Penulis : Dini Novita Sari
Penerbit : Bhuana Sastra (Imprint dari PT. BIP)
Cetakan : 2013
Tebal : 198 hlm
ISBN : 978-602-249-439-3
Novel Get Lost karya Dini Novita Sari ini mengisahkan tentang Lana Sagitaria, seorang pegawai swasta yang dalam kesehariannya terjebak dalam ritme rutinitas kerja yang membosankan. Sebagai pengusir rasa jenuhnya Lana selalu menyempatkan diri melakukan perjalanan ke berbagai tempat, bertemu dengan orang-orang asing, memperhatikan situasi dimana dia berada yang membawanya pada pengalaman-pengalaman baru yang tentunya lebih indah dibanding terjebak dalam kursi kubikelnya sambil menatap layar komputer yang menampilkan file-file yang haru dikerjakannya.
"Aku senang merasakan atmosfer baru, senang mendengarkan percakapan orang-orang setempat dengan bahasa yang tak jamak kudengar dan logat yang walau di awal terasa aneh, tetapi akhirnya menjadi terbiasa layaknya nyanyian nan merdu. Aku senang memperhatikan sekelilingku."
Pengalaman Lana dalam melakukan berbagai perjalanan inilah yang dikisahkan penulis dalam novel perdananya ini. Ada 4 tempat yang Lana singgahi yaitu Bali, Singapura, Korea Selatan, dan Surabaya-Bromo, masing-masing tempat memiliki kisahnya sendiri yang menarik untuk disimak. Dari keempat kisah perjalannya ini, kenangannya akan Dharma, seorang pria yang Lana sayangi yang tiba-tiba saja menghilang dari kehidupannya menjadi benang merah yang membuat novel ini juga memiliki sisi romantisme
Dalam perjalanannya ke Bali dikisahkan Lana membiarkan dirinya berangkat tanpa persiapan yang mendetail. Salah satu yang telah direncanakannya hanyalah tanggal keberangkatan berdasarkan tiket yang pesawat yang telah ia pesan sebelumnya. Sedangkan tempat menginap, susuanan perjalanan, dll sama sekali tidak ia persiapkan karena ia ingin menantang dirinya sendiri yang selama ini serba terencana dan sering mengkhawatirkan hal-hal detail selama liburan. Intinya di perjalanannya kali ini Lana siap tersesat di tempat-tempat yang akan ia kunjungi.
Apa yang ia temui di Bali dengan perjalanan tanpa rencananya itu ternyata berbuahkan pengalaman-pengalaman yang tidak terduga dan menuntunnya untuk bertemu dengan orang-orang yang akan menngispirasi dirinya lewat percakapan-percakapan filosofis tentang kehidupan.
Lewat tuturan seorang teman yang baru dikenalnya, Lana mendapat pencerahan tentang kenangan akan masa lalunya yaiut kenangannya akan Dharma yang tiba-tiba saja menghilang dari kehidupannya.
"Tidak selamanya kenangan buruk itu hadir untuk menyakiti koq. Lan.Kadang itu ada untuk mengingatkan kita bahwa proses hidup itu sungguh nyata. Lo nggak perlu susah payah menyingkirkannya, sering kali yang kita butuhkan hanyalah iklhas" (hlm 34)
Sedangkan dari perkenalannya dengan seorang bapak yang menyediakan tempat baginya untuk menginap di Ubud Lana mendapat mencerahan akan pencarian jawaban dan tujuan hidup manusia.
"Manusia memang ditadirkan untuk mencari jawaban. Selalu ada pertanyaan yang menggelisahkan mereka. Yang tak kita ketahui, seringnya jawaban itu sudah tersedia di hadapan kita, tapi kita saja yang terlalu jauh mencarinya, hingga seolah tak tampak"
(hlm 36)
"Tapi bapak selalu bertanya, adakah tujuan hidup yang diberikan Tuhan kepada bapak sudah bapak capai? Pertanyaan itu yang lantas memacu semangat hidup bapak setiap hari, untuk menjadikan hari demi hari bapak berguna bagi diri sendiri dan juga orang lain, sehingga pertanyaan tentang tujuan hidup itu akan terjawab dengan sempurna secara perlahan-lahan"
(hlm 42)
Di perjalanannya yang kedua, Lana kini tersesat di Singapura. Dalam perjalanannya kali ini Lana kehilangan kertas tempat ia mencatat nama dan alamat apatemen milik kawan lamanya. Beruntung ia bertemu dan berkenalan dengan Paul, pemuda bule yang mengajaknya menginap di sebuah tempat bersama-sama kelompok turis lainnya. Paul ternyata memiliki kesamaan nasib dengan Lana yang ditinggal secara tiba-tiba oleh kekasihnya. Hal ini membuat mereka menjadi semakin akrab. Melalui persahabatannya dengan Paul di Singapura, Lana belajar bahwa cinta sejati sepasang anak manusia akan pada akhirnya berlabuh di sebuah tempat walau harus melalui jalan yang panjang dan berliku.
 Jika di Singapura Lana berusaha membantu Paul menemukan kekasihnya yang hilang , maka di Seoul, Korea Lana membantu Kang Soo Jung, seorang kenalan sahabatnya dimana Lana menginap selama di Korea untuk mencari hanbok (pakaian tradisional Korea) warisan nenek buyutnya yang hilang dicuri mantan kekasih Jung. Mereka berdua bersama-sama menjelajah Busan demi menemukan hanbok tersebut.
Jika di Singapura Lana berusaha membantu Paul menemukan kekasihnya yang hilang , maka di Seoul, Korea Lana membantu Kang Soo Jung, seorang kenalan sahabatnya dimana Lana menginap selama di Korea untuk mencari hanbok (pakaian tradisional Korea) warisan nenek buyutnya yang hilang dicuri mantan kekasih Jung. Mereka berdua bersama-sama menjelajah Busan demi menemukan hanbok tersebut.Berbeda dengan pernjalanannya ke Bali, Singapura, yang memang diniatkan Lana untuk mengusir kejenuhannya dan kepergiannya ke Korea karena memenangkan tiket gratis dari sebuah quiz di internet, perjalanan berikutnya ke Surabaya dan Bromo dikarenakan sebuah telpon dari seseorang yang bernama Kresna yang mengaku memiliki pesan yang dititipkan Dharma kepadanya dan pesan itu harus disampaikan secara langsung kepada Lana. Dengan perasaan yang tak menentu Lana ditemani teman dekatnya, berangkat ke Surabaya lalu ke Bromo untuk menerima pesan dari kekasihnya. Di bagian ini juga melalui kisah Dharma kita akan diajak mengunjungi Tibet yang karena ketinggiannya berada di sekitar 4.500 meter di atas permukaan laut, membuat Tibet menyandang gelar sebagai atap dunia.
Satu hal yang menarik di bagian ini adalah ketika Dharma bercerita tentang desa di bukit Xishan, China yang dihuni oleh sekitar 100 orang bertubuh kerdil.
"Di sana ada sebuah desa yang bernama Dwarf Empire. Memasuki desa ini kami merasa bahwa diri kami adalah serupa raksaksa, kenapa? Karena segala sesuatu di desa ini bentuknya mini, kecil. Desa ini dihuni sekitar 100 orang bertubuh kerdil. Dan segala sesuatu yang ada di desa ini pun menyesuaikan dengan bentuk tubuh mereka. Rumah sampai fasilitas-fasilitas yang ada berukuran mini. Lalu, dalam dua hari sekali mereka membuat pertunjukan semacam karnaval untuk menarik para wisatawan... Aku senang melihat bentuk kepercayaan diri mereka, dan juga cara bergaul mereka dengan para wisatawan"
(hlm 174-175)
Keempat kisah diatas tersaji secara menarik, sebagai sebuah novel fiksi perjalanan penulis tidak hanya menyuguhkan deksripsi tentang lokasi, makanan, penduduk, dari masing-masing tempat yang disinggahi tokohnya melainkan mencoba menghidupkan kisahnya dengan sisi petualangan Lana lengkap dengan sisi romantisme kenangan dan pencariannya akan Dharma, kekasihnya.yang hilang.
Selain itu di setiap kisahnya juga penulis memberi muatan-muatan perenungan filosofis terlebih di perjalanan Lana ke Bali sehingga pembaca akan mendapat 'sesuatu' dari membaca novel ini. Dalam buku ini juga penulis mengungkap dan mempertanyakan perlakuan diskriminasi yang dilakukan orang Bali terhadap turis lokal dimana turis asing lebih dihargai dan diutamakan pelayanannya dibanding turis lokal.
"Jadi masih sebegitu superiorkah warga negara asing di mata penduduk Indonesia sendiri? Bukankah seharusnya saudara sendiri lebih diutamakan daripada orang asing?"
(hlm 15)
Yang agak disayangkan dari novel ini adalah ada banyak faktor keberuntungan dan kebetulan dalam petualangan Lana seperti misalnya keberuntungan Lana memenangkan kuiz di twitter yang akan membawanya ke Korea
"Iya, seingatku sih waktu itu iseng-iseng aja jawab pertanyaan dari akun @AwesomeKorea. Udah dua bulan lalu, bo dan aku aja udah lupa! Tahu-tahu muncul pengumuman ini satu jam yang lalu..." (hlm 91)
"..aku berhak atas atas hadiah tiket pesawat pulang pergi ke Seoul menggunakan maskapai berlayanan penuh! Lebih hebatnya lagi, aku juga diberi uang saku sejumlah lima juta rupiah untuk lima hari berada di Korea Selatan"
(hlm 92)
Betapa beruntungnya Lana yang hanya bermodalkan iseng-iseng saja akhirnya ia bisa berangkat ke Korea. Apakah memang ada quiz yang hanya menjawab pertanyaan lalu mendapat hadiah sebesar itu?
Lalu ada pula faktor kebetulan yang menunguntungkan lainnya seperti bertemunya tokoh-tokoh yang memang sedang dicari saat itu secara kebetulan (agar tidak menjadi spoiler saya sengaja tidak menyertakan contoh2nya). Faktor kebetulan dalam sebuah novel memang tidak salah dan sangat mungkin dialami kita semua di dunia nyata , namun jika dalam sebuah novel kita menemukan beberapa kali faktor kebetulan tentunya hal itu membuat kisah atau konflik yang sudah dibangun menjadi kurang 'greget' penyelesaiannya.
Kemudian ada hal yang menurut saya kurang bisa diterima yaitu tentang Dharma yang mencoba mendaki pegunungan Himalaya. Di sepanjang kisahnya tidak dikisahkan bahwa Dharma adalah juga seorang pendaki gunung, lalu ketika ia sampai di Tibet tiba-tiba saja ia memiliki keinginan untuk menaklukkan puncak Everest, puncak tertinggi di dunia dan mencobanya.
Mendaki puncak Everest, puncak tertinggi di dunia dengan ketinggian 6.199 meter di atas permuakaan laut tentu saja berbeda dengan mendaki gunung-gunung lainnya,dibutuhkan persiapan yang matang baik dari segi fisik, mental, maupun peralatan. Di sini penulis tidak menyinggung hal tersebut sama sekali sehingga apa yang dilakukan Dharma yang bukan seorang pendaki gunung menjadi seolah tidak masuk akal.
Kesalahan kecil juga terdapat dalam novel ini, yaitu soal penyebutan Jacky Chan sebagai artis yang bisa ditemui di Taiwan.
"Ke Taiwan," jawab Alvin sambil menoleh dari jok ke depan. "Dia mau ketemu Jacky Chan, Lan, mau berguru kungfu..."
(hlm 28)
Satu hal lagi adalah tentang hanbok (pakaian tradisional Korea) yang muncul dalam perjalanan Lana ke Seoul. Alangkah baiknya jika penulis mengeksplorasi lebih dalam tentang hanbok ini, pastinya ada sesuatu yang bisa kita ambil dari pakaian tradisional Korea ini lebih dari sekedar baju tradisional yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek buyut Jung.
Terlepas dari kekurangannya novel ini patut diapresiasi dengan baik karena novel ini tidak hanya menghibur pembacanya saja melalui petualangan Lana yang tersesat di berbagai tempat. Seperti judulnya Get Lost, novel ini menantang pembacanya untuk keluar dari rutinitas, melakukan perjalanan seorang diri tanpa persiapan matang, membiarkan diri tersesat untuk dituntun oleh semesta untuk mendapat pengalaman hidup yang barui dalam setiap perjalanan, terbuka menerima kehadiran orang-orang asing yang masuk dalam kehidupan kita sambil belajar dan berkaca akan diri.
Dan seperti apa yang dialami Lana, dalam ketersesatan di tempat-tempat yang asing bukan tidak mungkin kita akan menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan tentang kehidupan yang selama ini terpendam dalam lubuk hati kita masing-masing.
Berani mencoba?
@htanzil






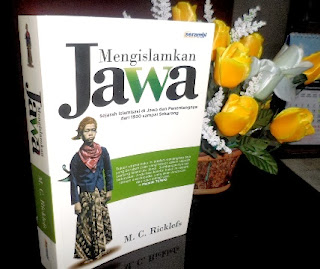































.jpg)














